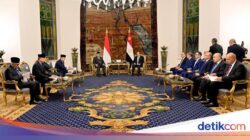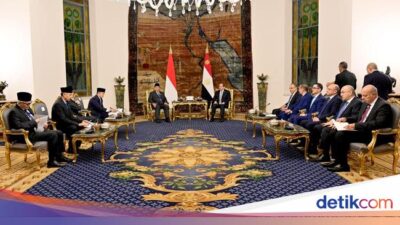Jakarta –
Presiden Iran Massoud Pezeshkian telah memveto undang-undang jilbab yang baru-baru ini disahkan oleh parlemen. Dewan Keamanan Nasional – badan pengambil keputusan tertinggi di Iran mengenai masalah keamanan- menangguhkan undang-undang tersebut.
Pezeshkian berharap undang-undang itu setidaknya sebagian direvisi. Menurut harian Hamshahri, penasihat presiden Ali Rabiei membenarkan langkah ini dengan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi sosial dari undang-undang tersebut.
Undang-undang tersebut, yang didorong oleh kelompok Islam garis keras di parlemen, menjatuhkan hukuman berat bagi perempuan yang melanggar kewajiban mengenakan jilbab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini termasuk denda yang tinggi, penghentian layanan publik, dan menargetkan orang-orang terkemuka berupa larangan profesional dan perjalanan, serta penyitaan aset hingga lima persen.
Dalam beberapa minggu terakhir, para profesional media, guru dan aktivis anak telah mengeluarkan beberapa pernyataan yang menyerukan penangguhan undang-undang hijab yang kontroversial.
Mereka menggambarkan undang-undang tersebut sebagai “penghinaan terang-terangan” terhadap masyarakat dan memperingatkan konsekuensi sosialnya.
Sengketa makin mengemuka
Dalam debat di platform Azad Media, profesor hukum pidana Mohsen Borhani dengan tajam mengkritik undang-undang tersebut pada tanggal 9 Desember lalu: “Dengan undang-undang semu seperti itu, parlemen semakin memecah-belah masyarakat.”
Borhani, yang ditangkap dan diskors dari Universitas Teheran pada tahun 2023 karena kritiknya terhadap sistem politik, kembali mendapatkan posisinya di bawah kepemimpinan Presiden Massoud Pezeshkian. Pengacara dan kriminolog tersebut kini memperingatkan konsekuensi dari undang-undang hijab yang tidak hanya melanggar hak-hak sipil, tetapi juga melemahkan keimanan terhadap agama.
Para pengamat juga melihat perselisihan mengenai undang-undang tersebut sebagai perebutan kekuasaan antara kelompok garis keras dan kekuatan moderat. Selama kampanye pemilu, Presiden Pezeshkian berjanji untuk mengambil tindakan yang lebih moderat.
Peseschkian juga tidak siap untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan perempuan, ujar aktivis hak asasi manusia dan mantan jurnalis Faezeh Abdipour dalam wawancara dengan DW. Sejak Revolusi Islam pada tahun 1979, perempuan diwajibkan mengenakan jilbab. Undang-undang baru ini sekarang dimaksudkan untuk memperketat hukuman secara drastis.
Abdipour, yang telah ditangkap beberapa kali karena komitmennya terhadap agama minoritas dan hak asasi manusia, menekankan: “Perempuan di Republik Islam telah belajar untuk berjuang setiap hari dan secara konsisten demi kebebasan dan kehidupan mereka. Mereka ingin memutuskan sendiri apa yang mereka kenakan. Namun sayangnya sistem politik sepertinya tidak akan menyerah pada masalah ini.”
Situasi bagi perempuan yang menolak berhijab kini semakin memprihatinkan. “Ada patroli polisi moral di kereta bawah tanah dan di persimpangan, denda dan tilang bagi mereka yang tidak mengenakan jilbab,” lapor Abdipour. Mobilnya sendiri disita beberapa bulan lalu karena ‘pelanggaran’ kewajiban berjilbab. “Denda yang harus saya bayar sangat tinggi,” tambahnya.
“Perempuan yang bersuara di depan umum atau memposting foto tanpa jilbab di media sosial ditekan untuk menghapus konten, sering kali di bawah ancaman konsekuensi hukum. Mantan narapidana – seperti saya – juga terus dianiaya oleh otoritas keamanan.”
Perubahan sosial
Di kota-kota besar Iran, banyak perempuan yang tidak lagi mematuhi aturan berpakaian islami yang ketat. Tren ini menyusul protes massal pada musim gugur tahun 2022 yang menggerakkan opini global dengan semboyan ‘Perempuan, kehidupan, kebebasan’.
Politisi dari kalangan konservatif, seperti mantan pimpinan parlemen Ali Larijani, orang kepercayaan pemimpin agama Ayatollah Khamenei, juga mengkritik undang-undang jilbab yang baru karena tidak menjadi jawaban yang tepat terhadap tren ini. “Kami tidak membutuhkan undang-undang seperti itu, tapi yang paling kami butuhkan adalah persuasi budaya,” tegas Larijani.
Namun justru kebijakan persuasi budaya inilah yang gagal, ujar aktivis Shiva Kianfar. Kianfar, yang melarikan diri ke Jerman karena penindasan negara, melihat protes tahun 2022 sebagai titik balik: “Sejak demonstrasi nasional, pemikiran ulang telah terjadi di masyarakat. Banyak keluarga kini berpihak pada perempuan yang tidak lagi mau tunduk.”
Selama aksi protes tahun 2022, Kianfar ditangkap di Kota Urmia dan menghabiskan beberapa bulan di Penjara Urmia yang terkenal kejam. “Bahkan di sana, kami menolak mengenakan jilbab di depan interogator kami,” kenangnya.
Dia dan keluarganya harus membayar mahal atas perlawanan mereka; mereka hanya dibebaskan dengan jaminan dan terus berada di bawah tekanan setelahnya. Bagi Kianfar, perlawanan perempuan yang terus berlanjut merupakan ekspresi dari perubahan sosial yang mendalam – sebuah perubahan yang ia yakini tidak dapat lagi dihentikan.
*Artikel diterjemahkan dari bahasa Jerman
(ita/ita)