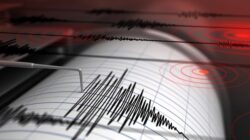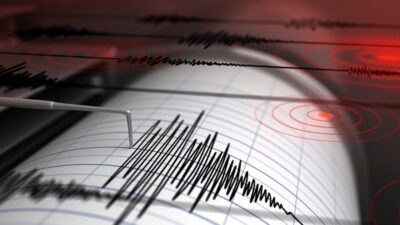Banyak video beredar di media sosial yang memperlihatkan anak-anak sekolah kesulitan menjawab pertanyaan pengetahuan umum dan dasar yang sewajarnya dikuasai anak sekolah. Misalnya, sekelompok anak yang diberi pertanyaan tentang singkatan. Atau video lain tentang sekelompok murid yang kesulitan melakukan pembagian bilangan puluhan dengan bilangan satuan. Juga video tentang sekelompok anak yang tidak mengetahui nama negara-negara di sebuah benua. Termasuk fakta menegangkan yang muncul di kabar berita televisi nasional tentang anak-anak jenjang SMP yang belum bisa membaca.
Yang menjadikan fenomena ini menarik adalah peran media sosial tempat semua orang dari berbagai kalangan, latar belakang, dan kepentingan bisa berkomentar apapun mengenai fenomena tersebut. Tidak perlu punya keahlian khusus, kepakaran mendalam, latar belakang akademik mentereng, atau pengalaman berkecimpung di bidang pendidikan bertahun-tahun supaya bisa mengeluarkan pendapat tentang fenomena ini. Siapapun yang terhubung ke platform digital tertentu tempat video tersebut tersebar bisa berkomentar dan komentarnya bisa setara dengan pakar di bidang pendidikan.
Bagi pihak yang gemar mengkritik pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, fenomena ini dikaitkan dengan kegagalan Kurikulum Merdeka yang diterapkan pada era Menteri Nadiem Makarim. Kurikulum Merdeka diklaim sebagai kurikulum yang terlalu bebas karena berpihak pada murid, salah satunya dengan tetap membiarkan murid naik kelas meskipun tidak bisa membaca, merupakan penyebab utama mengapa anak-anak tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan tentang pengetahuan umum dan mendasar.
Selain itu dihilangkannya Ujian Nasional (UN) pada 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia dituding sebagai bagian dari kegagalan Kurikulum Merdeka. Menurut warganet yang mengkritik kebijakan ini, murid menjadi tidak memiliki motivasi belajar karena tidak ada UN. UN yang salah satu fungsinya untuk menentukan kelulusan murid dari satu jenjang pendidikan dianggap efektif sebagai alat untuk memotivasi murid belajar sehingga memiliki skil dan pengetahuan tertentu yang dibutuhkan.
Tetapi kelompok yang pro dengan kebijakan pemerintah punya alasan tersendiri. Dalil utama yang diberikan cukup valid. Usia anak-anak yang muncul di video berada di kisaran usia SMP dan SMP, yang berarti bahwa setidaknya anak-anak telah bersekolah selama minimal 6 tahun bahkan 9 tahun. Atas dasar itulah, menyalahkan penghapusan UN dan Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan secara bertahap pada 2021 merupakan tuduhan yang salah alamat.
Jika anak-anak sudah bersekolah minimal 6 tahun, kurikulum mana yang pantas disalahkan? Jika mereka sudah sampai di jenjang SMA, setidaknya mereka pernah menempuh salah satu UN entah di jenjang SD atau SMP, apakah UN menjadikan mereka tahu pengetahuan umum dan pengetahuan dasar tersebut?
Upaya Cocoklogi
Sebagai guru yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan dan persekolahan selama 10 tahun, memutuskan untuk menghubungkan fenomena yang terjadi di kalangan anak sekolah dengan kebijakan kurikulum dan UN sangatlah sulit. Terutama karena saya kesulitan menemukan hasil penelitian yang membahas hal tersebut. Tanpa adanya data seperti itu, saya meyakini bahwa upaya menghubungkan anak yang tidak hafal persamaan Pythagoras atau tidak tahu nama negara di Eropa dengan kebijakan kurikulum dan UN hanyalah upaya cocoklogi.
Tanpa adanya data valid, hal tersisa yang saya punya adalah pengalaman. Sepuluh tahun berkecimpung di dua sekolah dengan latar belakang geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda membuat saya meyakini validitas pengalaman saya. Meskipun, pada awal saya harus membuat klaim bahwa validitas ini hanyalah validitas internal dan karenanya hanya berlaku dalam konteks di mana saya berada.
Saya akan memulai dari pengalaman pada 2019 kemudian bergerak mundur ke belakang. Pada tahun itu saya baru saja pindah ke sebuah SMP baru yang tidak jauh dari pusat kabupaten di salah satu kabupaten di DIY, sebuah sekolah berbasis pesantren dengan murid berasal dari berbagai kota di Pulai Jawa. Saat itu masih berlaku Kurikulum 2013 yang direvisi pada 2017.
Sebagai guru IPA, semester pertama saya mengajar materi suhu dan kalor di mana salah satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah melakukan konversi suhu. Konversi suhu merupakan upaya membandingkan dua skala termometer, dan karena ini perbandingan maka muncullah pembagian. Dengan asumsi murid-murid saya telah melalui UN tingkat SD (saat itu disebut USBN), seharusnya mudah bagi mereka melakukan pembagian sederhana. Faktanya? Saya masih mendapati lebih dari setengah anggota kelas kesulitan melakukan operasi pembagian dan perkalian sederhana tersebut.
Mundur ke tahun 2014, tahun pertama saya mengajar. Saya mendapat kesempatan mengajar di sebuah SMP berbasis pesantren di pesisir timur Lampung, tepat di salah satu ruas Jalinsum Kabupaten Lampung Timur. Ketika pertama kali mengajar di sana masih masa transisi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menuju ke Kurikulum 2013. Dengan asumsi murid-murid saya di Kelas 7 melewati masa 6 tahun SD mereka dengan menggunakan KBK, tentunya mereka sudah mahir dengan pengetahuan dan penghitungan dasar. Faktanya, lagi-lagi saya harus menggelengkan kepala.
Dalam konteks pengalaman inilah akhirnya saya meyakini tidak ada korelasi yang kuat antara kebijakan kurikulum dan UN dengan pengetahuan umum dan dasar murid. Pengalaman mengajar di dua sekolah berbeda secara letak geografis dan latar belakang keluarga dari murid-muridnya meyakinkan saya bahwa fenomena yang saya temukan saat itu sama sekali tidak terhubung dengan kurikulum yang sedang diterapkan maupun ada atau tidaknya UN.
Bahkan jika saya mundur lebih jauh ke 2008 dan 2004 saat saya sebagai murid menjalankan UN, banyak materi dasar yang saya dan teman-teman saya tidak pahami dan banyak pengetahuan umum yang tidak kami ketahui. Lantas, apa yang sebenarnya mempengaruhi pengetahuan dasar seorang murid?
Banyak Faktor
Menjawab pertanyaan tersebut tidak bisa serta merta menunjuk satu atau dua variabel sebagai penyebabnya karena banyak faktor yang terlibat dalam proses penguasaan pengetahuan dasar seseorang.
Bisa dari faktor internal anak (kemampuan kognitif, karakter rasa ingin tahu, daya tahan dalam mencari tahu), faktor pengasuhan keluarga (seberapa banyak stimulus yang didapatkan anak pada masa balita yang merangsang perkembangan otak dan karakternya), faktor lingkungan rumah (pergaulan sosial anak di rumah), faktor lingkungan sekolah (pergaulan sosial anak di sekolah), faktor budaya sekolah tempat dia belajar (sekolah yang berfokus pada pencapaian akademik atau bukan), faktor guru-guru yang mengajar (guru yang melayani kebutuhan murid atau tidak), hingga faktor kebijakan pendidikan yang dicanangkan pemerintah termasuk UN.
Melihat kompleksitas itu, menuding satu atau dua faktor saja sebagai penyebab tentu tidak fair. Terlebih lagi sampai saat menulis artikel ini saya masih kesulitan menemukan hasil penelitian akademik maupun lembaga-lembaga penelitian yang secara definit menyebutkan bahwa kebijakan kurikulum dan UN mempengaruhi penguasaan pengetahuan dasar murid.
Yang saya yakini sebagai seorang guru adalah fenomena anak murid SMA tidak bisa melakukan operasi hitung dasar dan tidak tahu nama negara Eropa serta singkatan-singkatan umum, ditambah dengan fenomena murid SMP tidak bisa membaca dan menulis, adalah fenomena nyata dan meresahkan. Dan, karenanya fenomena ini harus segera dicarikan solusinya.
Beberapa pengetahuan umum seperti nama negara atau singkatan-singkatan bisalah kita kesampingkan terlebih dahulu karena relevansinya dengan masa depan murid tidak terlalu esensial. Yang harus menjadi fokus utama adalah kemampuan membaca dan menghitung dasar. Keduanya merupakan skill mendasar yang harus dikuasai murid dalam menghadapi masa depan. Ketimbang menunggu kebijakan pemerintah yang rumit dan seringkali tidak sesuai dengan kondisi lapangan, saya mengajak teman-teman guru yang menemukan fenomena seperti itu saling bekerja sama dengan sesama rekan guru di sekolah.
Sekolah sebagai unit terkecil pendidikan formal harus bekerja sama dengan orangtua sebagai unit terkecil pendidikan anak mengupayakan berbagai strategi untuk mengejar ketertinggalan yang dialami anak. Entah mengadakan kelas tambahan di sekolah, mengadakan berbagai aktivitas yang bisa merangsang kemampuan membaca dan menghitung secara terpisah, sambil memberikan edukasi kepada orangtua yang bersangkutan bahwa proses yang sedang berlangsung harus dilalui agar anak tidak kehilangan haknya di masa depan.
Jika kita punya begitu banyak energi untuk berdebat panjang di media sosial tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, bukankah seharusnya kita juga punya energi yang begitu banyak untuk mengupayakan bantuan terbaik bagi anak-anak kita yang sedang mengalami tantangan besar dalam salah satu fase pendidikannya?